Oleh : Robith Ilman
Berjutapena.or.id – Di berbagai ruang pertemuan, baik di komisariat sekolah maupun rapat-rapat kecil di tingkat kecamatan, percakapan yang paling sering terdengar dari para pengurus IPNU–IPPNU Situbondo hari-hari ini adalah tentang “kader yang ngomongin kader lain”, “anggota yang tidak loyal”, dan “pengurus yang bingung mau bergerak ke mana”. Nada keluhannya beragam, tetapi benang merahnya sama: gerakan pelajar NU seperti kehilangan arah. Bukan karena programnya sedikit, bukan karena kegiatan tidak berjalan, tetapi karena ada sesuatu yang lebih dalam dan lebih mendasar yang secara perlahan memudar—identitas.
Krisis identitas ini tidak muncul dalam sekejap. Ia lahir dari serangkaian gejala yang tampak kecil namun saling terhubung: pemahaman PD/PRT yang dangkal, penggunaan istilah Aswaja yang hanya menjadi jargon tanpa pedoman, proses kaderisasi yang cenderung repetitif dan berjarak dengan realitas, serta budaya senioritas yang sulit dibendung. Yang lebih mengkhawatirkan, generasi muda pelajar NU kini hidup dalam dunia yang berubah begitu cepat, namun organisasi yang mestinya menjadi tempat mereka belajar beradaptasi justru sering macet oleh cara pandang lama dan praktik yang tidak lagi sesuai dengan zaman.
Padahal, sejak awal berdirinya, IPNU–IPPNU tidak dibentuk untuk menjadi organisasi yang kaku dan seremonial. Sejarah pencetusan khitthah pelajar jelas: IPNU ditegaskan kembali sebagai organisasi kader pelajar pada Kongres XIV di Surabaya setelah melalui perjalanan panjang sejak era Makassar. Penegasan bahwa organisasi ini harus “kembali ke pelajar” bahkan dianggap sebagai keputusan paling penting dalam menghadapi kompleksitas tantangan zaman. Dokumen Kongres menggambarkan keputusan itu sebagai upaya mengembalikan IPNU pada identitas sejatinya, yakni wadah pemberdayaan pelajar yang dipandang sebagai “aset masa depan” NU.
Namun yang terjadi di banyak tempat, termasuk Situbondo, khitthah itu perlahan kabur karena berbagai hambatan internal organisasi sendiri. Padahal, dokumen Kongres XX menegaskan bahwa tertib organisasi hanya mungkin dijalankan jika PD dan PRT benar-benar dijadikan pedoman operasional. Tanpa itu, gerakan mudah kehilangan disiplin, tujuan, bahkan marwah. Di dalam dokumen resmi disebutkan bahwa PD/PRT disahkan sebagai pedoman yang harus menjadi dasar langkah organisasi di semua tingkatan. Krisis orientasi yang terjadi di Situbondo jelas menunjukkan bahwa pedoman ini belum benar-benar menjadi pegangan. Banyak pengurus mengakui bahwa mereka “pernah menerima PD/PRT” tetapi tidak pernah sungguh-sungguh membaca atau mendiskusikannya. Alhasil, aturan tidak menjadi referensi, dan ruang kosong itu diisi oleh budaya informal: senioritas yang berlebih, penafsiran aturan berdasarkan pengalaman pribadi, dan keputusan yang lebih banyak bergantung pada “kata orang” daripada dokumen resmi organisasi.
Masalah berikutnya adalah bagaimana proses kaderisasi dijalankan. Dalam berbagai kesempatan, para peserta MAKESTA atau LAKMUD mengeluhkan bahwa materi yang diberikan sering kali terlalu teoritis, tidak kontekstual, atau berulang dari tahun ke tahun. Padahal Kongres telah menegaskan bahwa IPNU harus menjadi “learning organization”—organisasi pembelajaran yang progresif, inovatif, kreatif, dan profesional. Dalam naskah Kongres disebut bahwa kader harus terus mengembangkan diri dan sistem kerja organisasinya dalam kerangka transparansi dan akuntabilitas.
Jika prinsip ini benar-benar diterapkan, proses kaderisasi tidak akan terasa stagnan. Akan ada inovasi, penyesuaian metode, dan pembaruan kurikulum yang menghubungkan Aswaja dengan realitas sosial kontemporer. Tetapi di Situbondo, proses kaderisasi sering sebatas acara formal yang mengulang materi lama, tanpa ruang diskusi kritis, tanpa refleksi nilai, dan tanpa penguatan kemampuan adaptif.
Di tengah situasi seperti ini, wajar jika muncul fenomena kader-kader yang “datang ketika butuh sertifikat” atau “aktif hanya ketika ada kegiatan besar”. Loyalitas menjadi lemah, bukan karena kader tidak punya minat, tetapi karena mereka tidak merasakan hubungan emosional dan intelektual yang cukup dengan organisasi. Kader merasa IPNU–IPPNU tidak menawarkan ruang perkembangan yang nyata; mereka tidak merasakan bahwa organisasi ini membantu mereka tumbuh sebagai pelajar yang kritis, religius, dan produktif. Padahal, dalam dokumen Jati Diri IPNU, kader ideal digambarkan sebagai insan rabbani yang tidak hanya berilmu, tetapi juga berakhlak, berpandangan luas, serta memiliki orientasi pengabdian kepada masyarakat dan bangsa. Kesenjangan antara nilai ideal dan praktik aktual inilah yang memunculkan apa yang di esai ini saya sebut sebagai krisis identitas kader.
Krisis Identitas Itu Bernama “Disorientasi”
Disorientasi ini muncul dari tiga sumber utama. Pertama, jarak antara dokumen ideologis dan praksis organisasi. Kedua, pola komunikasi yang didominasi oleh struktur senioritas yang kaku. Ketiga, absennya ruang refleksi dan kritik. Dalam dokumen Kongres, mekanisme kritik-otokritik justru ditekankan sebagai bagian dari budaya organisasi. Disebutkan bahwa kritik-otokritik penting untuk mencegah penyimpangan dan menjaga keberlangsungan program organisasi.
Sayangnya, di banyak tingkatan, kritik masih dianggap ancaman. Kader yang mencoba menyuarakan pendapat sering dianggap “kurang ajar”, “belum saatnya bicara”, atau “tidak tahu apa- apa tentang organisasi”. Kultur seperti ini tidak selaras dengan nilai Aswaja yang adaptif dan ilmiah, serta tidak selaras pula dengan paradigma IPNU yang menempatkan dirinya sebagai organisasi progresif dan kolaboratif. Kongres bahkan menegaskan bahwa kader harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan membuka diri untuk bekerja sama dengan berbagai pihak selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar IPNU.
Disorientasi itu semakin dalam ketika proses kaderisasi tidak memberi ruang bagi kader untuk memahami sejarah, identitas, dan tujuan organisasi secara utuh. Padahal IPNU mempunyai sejarah yang panjang, mulai dari fase khitthah 1954 hingga berbagai muktamar yang menegaskan posisi IPNU sebagai garda terdepan kaderisasi Nahdlatul Ulama di tingkat pelajar. Naskah Kongres menjelaskan secara detail bagaimana IPNU sejak awal adalah wadah perjuangan pelajar NU untuk menyosialisasikan nilai keislaman, kebangsaan, dan keilmuan.
Jika sejarah ini tidak ditanamkan dalam kesadaran kader, wajar bila banyak di antara mereka memandang IPNU–IPPNU hanya sebagai organisasi seremonial yang tugasnya menyelenggarakan lomba, apel, atau pertemuan rutin. Mereka kehilangan rasa keterhubungan dengan mandat historis dan mandat keilmuan organisasi.
Membaca Ulang Nilai: Kembali ke Khitthoh sebagai Jalan Pemulihan
Untuk keluar dari krisis identitas ini, langkah pertama dan paling mendasar adalah melakukan pembacaan ulang terhadap naskah dasar organisasi. Rereading ini bukan sekadar membaca teks, tetapi memahami nilai dan konteksnya, lalu mengembalikan seluruh gerak organisasi pada arah yang sesuai khitthah.
Landasan berfikir yang dijelaskan dalam Kongres menyebut bahwa kader IPNU harus memadukan dalil naqli, aqli, dan waqi’i. Artinya, organisasi ini menolak cara pandang yang ekstrem—baik ekstrem tekstual maupun ekstrem liberal. IPNU berdiri pada moderasi berpikir, di mana tradisi keagamaan, akal sehat, dan pengalaman sosial ditempatkan dalam satu kerangka utuh. Jika prinsip ini dibawa ke dalam kehidupan organisasi, maka setiap keputusan harus bersandar pada logika yang jelas, dalil nilai yang tepat, dan pembacaan realitas lapangan yang memadai. Keputusan tidak boleh diambil hanya karena “tradisi pengurus sebelumnya”, atau “kebiasaan di kecamatan sebelah”, atau “perintah senior”. Ia harus berbasis ilmu, nilai, dan konteks.
Landasan bersikap yang mencakup tauhid, ukhuwah, akhlak, dan keluhuran moral sebenarnya sudah cukup untuk menjadi penangkal budaya senioritas yang berlebihan. Dokumen Kongres menekankan pentingnya kejujuran, persaudaraan, dan keluhuran moral dalam berorganisasi. Jika nilai ini dijalankan, maka hubungan antara pengurus dan kader tidak akan bersifat hierarkis, melainkan edukatif. Senior tidak memerintah seenaknya; junior tidak menjalankan tugas karena takut dimarahi. Keduanya bekerja sebagai sesama pelajar yang merawat tradisi Aswaja dan mengembangkan organisasi bersama-sama.
Selain itu, paradigma organisasi yang progresif, adaptif, dan kolaboratif harus menjadi dasar kaderisasi. Kongres dengan tegas menjelaskan bahwa IPNU harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan bekerja sama dengan berbagai pihak selama nilai-nilai inti organisasi tetap terjaga. Artinya, organisasi ini tidak boleh terjebak pada pola lama yang membuatnya tertinggal. Jika dunia pelajar bergerak cepat dalam disrupsi teknologi, media digital, dan wacana sosial baru, IPNU tidak bisa hanya bergerak dalam pola acara konvensional. Kader harus dilatih untuk menguasai literasi digital, berpikir kritis, membaca fenomena sosial, dan merespons tantangan zaman sebagaimana prinsip “Belajar–Berjuang–Bertaqwa”.
Lebih jauh lagi, jati diri IPNU sebagai wadah pembentukan insan rabbani menuntut organisasi tidak sekadar menjadi tempat berkumpul, tetapi tempat menjadi manusia. Dalam dokumen Jati Diri IPNU dijelaskan bahwa organisasi ini bertujuan mencetak pelajar yang berilmu, berpandangan luas, berbudi luhur, dan mengamalkan ilmunya untuk masyarakat. Jika prinsip ini terintegrasi dalam kaderisasi di Situbondo, proses pelatihan tidak hanya berfokus pada materi struktural, tetapi juga pada pembentukan karakter, budaya intelektual, etika sosial, dan orientasi pengabdian.
Membenahi Sistem, Mengubah Budaya
Namun membaca ulang naskah saja tidak cukup jika tidak diikuti pembenahan sistematik. PD dan PRT memang telah disahkan sebagai pedoman operasional organisasi, tetapi implementasinya memerlukan struktur yang memadai. Dalam naskah Kongres dijelaskan bahwa PD/PRT menjadi dasar tertib organisasi, memastikan program dilakukan secara menyeluruh, terarah, dan terpadu.
Jika Situbondo ingin “kembali ke khitthoh” secara serius, maka setiap jenjang—PC, PAC, PK, PR— harus memastikan bahwa; Pertama, semua pengurus telah benar-benar memahami PD/PRT, Prinsip Perjuangan, Paradigma, dan Jati Diri. Kedua, kaderisasi disusun berdasarkan kurikulum yang terukur, tidak hanya mengulang modul lama. Ketiga, sistem kritik-otokritik dijalankan bukan sebagai formalitas, tetapi sebagai ruang belajar bersama. Keempat, kepemimpinan berjalan secara transparan dan akuntabel.
Khusus poin terakhir, Kongres menekankan bahwa pimpinan wajib mencerminkan suara anggota dan bertindak sebagai teladan, bukan sebagai penguasa struktural. Jika gaya kepemimpinan seperti ini dipraktikkan, kultur senioritas otomatis meluruh. Kader akan loyal bukan karena tekanan, tetapi karena kepercayaan. Mereka merasa dihargai, dilibatkan, dan diberi ruang berkembang.
Selain itu, Situbondo perlu memperkuat kolaborasi dengan sekolah dan pesantren. Naskah Kongres menjelaskan bahwa sekolah adalah institusi penting yang berfungsi sebagai “second school” bagi IPNU, tempat pendidikan kepemimpinan dan karakter bisa dikembangkan melalui kerja sama sinergis antara organisasi dan pihak sekolah. Di banyak tempat, PK yang aktif adalah yang berhasil menjalin komunikasi baik dengan pihak sekolah. Maka Situbondo harus menata ulang strategi relasi eksternal—bahwa IPNU bukan organisasi yang sekadar “meminjam aula”, tetapi partner pendidikan yang punya kontribusi nyata bagi siswa.
Intellectual Resilience: Jalan Meneguhkan Masa Depan
Dari seluruh uraian ini, dapat ditarik satu kesimpulan: gerakan pelajar NU Situbondo hanya akan menemukan kembali identitasnya jika para kader dan pengurus membangun Intellectual resilience (ketangguhan intelektual). Intellectual resilience bukan sekadar kemampuan membaca buku atau memahami teori, tetapi kemampuan menata cara berpikir, mengelola konflik nilai, memahami konteks, dan mengambil keputusan secara bijaksana dalam dinamika perubahan. Dalam tradisi NU, ketangguhan intelektual tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berpadu dengan ketangguhan moral dan spiritual. Konsep insan rabbani, sebagaimana dijelaskan dalam naskah Kongres, menggabungkan tiga unsur itu: ilmu, akhlak, dan pengabdian. Maka membangun kader solutif, adaptif, dan militan bukan dimulai dari memperbanyak program atau memperketat aturan, tetapi dari meneguhkan kembali relasi antara nilai, ilmu, dan aksi. Kader harus memahami mengapa organisasi ini didirikan, apa mandat sejarahnya, dan apa tujuan besar yang hendak dicapai. Tanpa itu, semua kegiatan hanya akan menjadi aktivitas di atas kertas.
Pelajar NU Situbondo, Inilah Momentum untuk Kembali ke Khitthoh
Situbondo punya modal besar: pesantren yang kuat, kultur religius yang hidup, jaringan pelajar NU yang luas, dan generasi muda yang punya potensi besar. Tetapi potensi itu hanya dapat berkembang jika organisasi memiliki arah yang jelas. “Kembali ke Khitthoh” bukan ajakan untuk bernostalgia. Ini seruan untuk merapikan kembali fondasi pergerakan. Kembali ke khitthoh berarti kembali pada:
- identitas asli sebagai organisasi pelajar,
- nilai Aswaja yang moderat dan rasional,
- paradigma progresif dan adaptif,
- jati diri insan rabbani,
- tradisi kritik dan pembelajaran,
- etika kepemimpinan yang jujur dan
Jika langkah ini ditempuh, Situbondo bisa menjadi contoh daerah yang berhasil menata ulang gerakan pelajar NU secara matang dan visioner. Para kader akan loyal bukan karena perintah, tetapi karena kesadaran moral, kecintaan terhadap ilmu, dan keyakinan bahwa organisasi ini benar-benar menjadi rumah intelektual dan spiritual mereka. Sebagai penutup, penulis ingin memberikan refleksi singkat bahwa:
“Khitthah bukan masa lampau yang ingin dihidupkan kembali, Ia adalah kompas masa depan yang menuntun pelajar NU Situbondo menuju gerakan yang relevan, berkarakter, dan berpengaruh”.










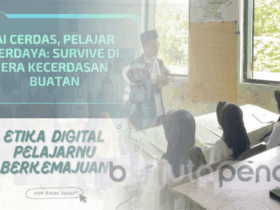
Leave a Reply